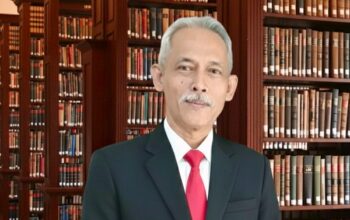Oleh : Junaidi Rusli — Wartawan Senior dan Pemerhati Kebijakan Publik
MITRAPOL.com, Jakarta – Suasana ruang sidang sering kali menjadi panggung bagi keadilan. Namun, di balik palu hakim dan toga hitam, publik menyaksikan paradoks yang mencolok: hukum yang seharusnya sama untuk semua, tampak tidak berlaku bagi sebagian aparat penegak hukum sendiri. Ketika rakyat kecil tersandung kasus gratifikasi, jeruji besi menanti. Tetapi ketika jaksa — penegak hukum itu sendiri — yang menerima, sanksinya justru ringan, bahkan sebatas pemindahan jabatan.
Dalam sistem hukum Indonesia, gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling sulit dibedakan dari hadiah biasa. Namun, yang kini menjadi sorotan publik adalah adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap penerima gratifikasi, terutama antara jaksa dan pejabat publik lainnya.
Kasus terbaru yang mencuat ke publik adalah dua eks Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat yang terbukti menerima gratifikasi senilai Rp500 juta. Alih-alih dijatuhi hukuman pidana berat, keduanya hanya diberikan sanksi administratif berupa pemindahan ke bagian Tata Usaha. Jumlah uang yang fantastis ini tentu kontras dengan kondisi masyarakat kecil, dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas penegakan hukum di tubuh kejaksaan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ancaman pidananya sangat berat: minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun, dan denda hingga Rp1 miliar.
Namun, dalam praktiknya, ketika pelaku gratifikasi berasal dari kalangan jaksa, penegakan hukum kerap kali lebih lunak dibandingkan pelaku dari kalangan ASN biasa, kepala dinas, atau kepala daerah. Sementara ASN atau pejabat publik lain yang menerima gratifikasi dengan nilai jauh lebih kecil bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan divonis penjara, para jaksa pelaku gratifikasi justru hanya dijatuhi sanksi etik atau penundaan promosi jabatan.
Padahal, jaksa seharusnya menjadi teladan integritas. Kode Etik Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Pedoman Perilaku Jaksa, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024, secara tegas melarang penerimaan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Ketika penegak hukum sendiri melanggar norma yang mereka tegakkan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum runtuh.
Fenomena Standar Ganda Penegakan Hukum
Perbedaan perlakuan ini mencerminkan adanya “double standard” dalam penegakan hukum. Hukum tampak keras bagi rakyat kecil dan pejabat biasa, tetapi menjadi lunak bagi aparat penegak hukum. Publik pun bertanya-tanya:
“Apakah hukum benar-benar sama di hadapan semua orang, ataukah berlaku asas ‘siapa yang menegakkan, dia yang dikecualikan’?”
Dampak Serius terhadap Kepercayaan Publik
Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Ketika masyarakat menyaksikan ketimpangan hukuman antara jaksa dan non-jaksa, kepercayaan terhadap supremasi hukum terkikis. Sistem hukum pun kehilangan wibawanya sebagai alat moral negara.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, transparansi dan konsistensi menjadi pondasi utama. Jika aparat penegak hukum justru dilindungi oleh institusinya sendiri, pemberantasan korupsi akan menjadi slogan tanpa makna.
Menegakkan Integritas Tanpa Tawar-Menawar
Komisi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memastikan penanganan kasus gratifikasi terhadap aparat penegak hukum tidak berhenti pada sanksi etik atau administratif.
Publik berhak menuntut proses pidana yang tegas dan transparan terhadap jaksa pelaku gratifikasi. Hanya dengan itu hukum akan kembali menjadi alat keadilan, bukan sekadar tameng kekuasaan.