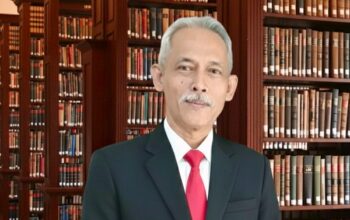Oleh: Sp. Rayrobbend Swr (Kabiro Mitrapol Sukabumi)
MITRAPOL.com, Sukabumi – Menjelang pesta demokrasi, wajah politik Indonesia kembali menampakkan sisi gelapnya. Bantuan sosial sering kali bukan datang dari keikhlasan negara membantu rakyat, melainkan sebagai alat tukar suara. Para politisi mendadak tampil sebagai sosok dermawan—membagikan beras, menyelipkan uang, dan melontarkan janji manis—semuanya demi satu tujuan: mendapatkan suara rakyat.
Fenomena ini bukan hal baru. Sejak era Orde Baru hingga reformasi, pola yang sama terus berulang. Jika dulu politik belas kasihan dikemas dalam bentuk proyek pembangunan, kini tampil lebih rapi lewat label bantuan sosial. Bentuknya boleh berganti, tetapi niatnya tetap sama: membeli simpati sebelum kotak suara dibuka.
Politik belas kasihan adalah manipulasi halus dalam demokrasi. Ia tidak memaksa, tetapi membujuk dengan perasaan. Ia tidak menindas, tapi merangkul dalam kepalsuan. Dalam praktik seperti ini, kemiskinan bukan dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan, melainkan sebagai komoditas politik yang sengaja dipertahankan.
Bayangkan, seorang ibu di pelosok Sukabumi menerima 10 kilogram beras dan amplop berisi Rp100 ribu. Ia merasa senang, namun tanpa sadar telah menandatangani “kontrak sosial tak tertulis”—mengikat nuraninya dengan rasa terima kasih palsu. Politisi tahu, rakyat lapar bukan hanya karena kurang makanan, tetapi karena minim pilihan.
Ketika rakyat sudah “dibayar”, sebagian politisi merasa tidak lagi punya kewajiban moral untuk melayani rakyat secara jujur. Mereka merasa telah membeli dukungan itu. Maka korupsi, penyimpangan anggaran, dan pengkhianatan janji sering terjadi setelah mereka duduk di kursi kekuasaan.
Yang menyakitkan bukan hanya mengapa politisi berani membeli suara, tetapi juga mengapa rakyat mau menjualnya. Jawabannya sederhana: kemiskinan membuat pilihan terasa mewah. Amplop kecil seakan menjadi mukjizat, padahal harga yang dibayar jauh lebih mahal—hak untuk menuntut keadilan setelah pemilu usai.
Demokrasi Indonesia pun terjebak dalam siklus murahan: uang ditukar suara, suara ditukar kekuasaan, kekuasaan ditukar proyek, proyek ditukar keuntungan pribadi. Sementara rakyat hanya menjadi penonton dari janji-janji sejahtera yang tak pernah terwujud.
Setiap lima tahun, rakyat mendengar lagu yang sama: janji membangun, janji menyejahterakan, janji memberantas korupsi. Namun begitu kursi kekuasaan dikuasai, janji-janji itu menguap menjadi lupa kolektif.
Inilah dosa struktural politik di negeri ini: sistem yang memberi ruang bagi tipu daya, bukan kejujuran. Selama suara bisa dibeli, maka harga keadilan akan terus murah.
Tugas media bukan hanya melaporkan, tapi juga menyadarkan. Media harus berani menulis hal-hal yang tak ingin didengar mereka yang berkuasa. Karena selama media memilih diam, politik belas kasihan akan terus hidup dan menindas dalam senyap.
Literasi politik rakyat harus diperkuat dari bawah: dari sekolah, masjid, pos ronda, hingga desa. Bukan dengan spanduk janji, tetapi dengan diskusi jujur tentang harga suara dan arti kehormatan.
Saya tidak menulis ini untuk pesimis. Saya menulis karena percaya masih ada orang baik di negeri ini—pejabat yang tulus bekerja, rakyat yang berani menolak uang haram demi masa depan anak-anaknya. Tapi harapan tidak cukup tanpa keberanian. Perubahan besar dimulai dari keputusan kecil: tidak menjual suara.
Kita mungkin tidak bisa menghentikan mereka yang ingin membeli suara, tapi kita bisa menolak menjual suara kita sendiri. Karena kadang yang kita kira rezeki, sebenarnya adalah tagihan yang kelak dibayar dengan korupsi.
Politik belas kasihan bukan sekadar strategi kampanye, tapi penyakit kronis demokrasi. Obatnya hanya satu: kesadaran rakyat bahwa martabat tidak bisa ditukar dengan uang. Ketika rakyat berani berkata “tidak”, maka kekuasaan yang lahir dari uang akan mati perlahan, tergantikan oleh kekuasaan yang lahir dari kepercayaan.